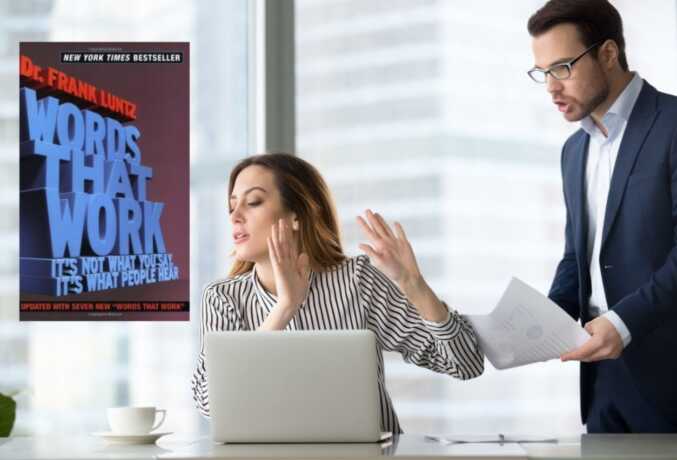Oleh: Edhy Aruman, Kolumnis, Lecturer and Educator LSPR Jakarta

PADA pertengahan 1990-an, publik Amerika dikejutkan dengan sebuah istilah hukum baru yang sebelumnya tidak pernah ada: accidental manslaughter.
Frasa itu diciptakan oleh pengacara Robert Shapiro saat membela Christian Brando, putra aktor Marlon Brando, yang terjerat kasus pembunuhan.
Shapiro tahu bahwa kata-kata adalah medan pertempuran utama dalam opini publik dan ruang sidang.
Kata “murder” terlalu keras, penuh konotasi gelap dan niat jahat. Untuk meringankan kliennya, dia menciptakan istilah baru yang melembutkan, menambahkan nuansa kemanusiaan: kematian bisa terjadi, tetapi tanpa niat.
Meski tidak memiliki pijakan hukum formal, Shapiro mengulanginya ratusan kali hingga media, publik, dan bahkan pengadilan mempercayainya.
Pada akhirnya, Brando mengaku bersalah bukan atas “murder” melainkan atas sesuatu yang terdengar lebih bisa diterima: accidental manslaughter.
Di sinilah terlihat betapa bahasa bukan hanya alat untuk menjelaskan realitas, melainkan juga alat untuk membentuk realitas itu sendiri.
Kekuatan kata juga muncul dalam pengalaman pribadi Frank Luntz saat ia masih menempuh pendidikan doktoralnya di Oxford.
Dalam sebuah pidato di Oxford Union Society, ia ingin menunjukkan betapa kejamnya pajak yang dipungut pemerintah.
Dengan percaya diri, ia mengeluarkan selembar uang kertas satu poundsterling dan mulai memotongnya di depan audiens.
Tak disangka, tindakannya itu ilegal dan dianggap sebagai pelecehan terhadap simbol nasional. Sorak-sorai berubah menjadi cemooh, dan Luntz merasa dipermalukan.
Sejak saat itu, ia tak pernah lagi berbicara di depan umum tanpa teks lengkap.
Insiden ini menjadi pengingat bahwa simbol, sama seperti kata-kata, bisa lebih sakral daripada yang tampak, dan komunikasi bukan hanya soal isi, melainkan juga soal konteks budaya.
Menulis buku Words That Work sendiri adalah ujian terberat bagi Luntz. Ia mengaku tidak bisa tidur nyenyak selama setahun, merasa tertekan oleh tuntutan dan ekspektasi.
Dalam keputusasaan, ia bahkan bergurau bahwa dirinya sempat berpikir untuk meminta bantuan Dr. Kevorkian, dokter yang terkenal dengan praktik euthanasia untuk mengakhiri penderitaannya.
Humor gelap itu menggambarkan betapa seriusnya ia memperjuangkan satu hal sederhana namun rumit, yakni menemukan kata-kata yang benar-benar bekerja.
Kata-kata semacam itu sering kali datang dalam bentuk yang paling sederhana. Dua kata yakni something wrong yang diucapkan Dr. Henry Lee dalam kasus O.J. Simpson adalah bukti nyata.
Saat ditanya tentang bukti DNA yang terkontaminasi, Dr. Lee dengan bahasa Inggris patah menjawab singkat, “Something wrong.”
Dua kata yang sederhana, jauh dari teknis, namun cukup kuat untuk mengguncang validitas bukti ilmiah yang rumit.
Kata-kata itu melekat di benak juri, mengubah arah opini, dan pada akhirnya turut memengaruhi hasil persidangan.
Luntz berulang kali menunjukkan bahwa komunikasi yang berhasil selalu menyentuh emosi, bukan sekadar logika.
Pada tahun 1994, ia membagikan 150 bola Nerf bertuliskan Talk to Me kepada politisi Republik. Bola kecil itu menjadi alat komunikasi yang mencairkan ketegangan antara politisi dan publik.
Dengan melemparkan bola ke arah audiens, pesan sederhana “bicaralah padaku” menjadi nyata, interaktif, dan personal.
Kata-kata yang dicetak di atas bola itu bukan hanya slogan, melainkan undangan untuk berhubungan.
Contoh lain ada di ranah bisnis. Industri perjudian lama dicap dengan kata “gambling,” penuh dengan asosiasi kriminalitas dan kecanduan.
Namun begitu kata itu diganti menjadi “gaming,” maknanya bergeser total. Mesin slot dan dadu tetap sama, tetapi publik mulai melihatnya sebagai bentuk hiburan.
Begitu pula dengan industri minuman keras yang mengganti istilah “liquor” menjadi “spirits,” menciptakan citra baru yang elegan, jauh dari bayangan pecandu alkohol.
Hanya dengan mengganti kata, persepsi publik berubah.
Bahasa juga bisa menjadi bumerang. Richard Nixon, dalam upayanya membela diri, berkata, “I am not a crook.”
Ironisnya, kalimat itu justru memperkuat persepsi publik bahwa ia memang seorang penjahat.
Demikian juga Jimmy Carter dengan pidato “krisis kepercayaan” yang kemudian direduksi media menjadi Malaise Speech, meskipun ia tak pernah menyebut kata “malaise.”
Publik mengingat bukan apa yang Carter katakan, melainkan apa yang mereka dengar dan tafsirkan.
Kisah-kisah ini mengajarkan pelajaran sederhana namun mendalam: kata-kata adalah kunci persepsi. Mereka bisa menyelamatkan reputasi, memperkuat bisnis, bahkan mengubah jalannya sejarah politik. Tetapi jika salah digunakan, kata-kata juga bisa menghancurkan seketika.
Luntz menegaskan bahwa inti komunikasi bukanlah retorika canggih atau argumen logis, melainkan empati. Komunikasi yang berhasil lahir dari pemahaman mendalam tentang harapan, ketakutan, dan pengalaman audiens.
Dalam konteks komunikasi politik modern, prinsip Luntz tetap sangat relevan. Politik hari ini lebih banyak ditentukan oleh sound bites dan frasa singkat yang viral ketimbang oleh argumen panjang.
Kata-kata seperti “fake news” atau “climate crisis” membentuk kerangka berpikir publik hanya dengan dua kata.
Prinsip Luntz bahwa “bukan apa yang Anda katakan, melainkan apa yang mereka dengar” menjadi semakin nyata di era media sosial, ketika pesan diproses dalam hitungan detik.
Di dunia bisnis, kekuatan bahasa juga tak kalah penting. Rebranding industri “gambling” menjadi “gaming” menunjukkan bagaimana kata dapat menghapus stigma.
Hal yang sama bisa kita lihat pada istilah “plant-based” yang kini jauh lebih diterima publik dibanding “vegan,” atau “sharing economy” yang lebih menarik dibanding “renting.”
Perusahaan yang menguasai narasi melalui bahasa bukan hanya menjual produk, tetapi menjual persepsi yang membentuk perilaku konsumen.
Secara akademik, karya Luntz selaras dengan teori framing dalam ilmu komunikasi yang dikemukakan oleh Erving Goffman dan diperluas oleh George Lakoff.
Kata-kata membentuk bingkai kognitif yang memengaruhi bagaimana orang memahami sebuah isu.
Seperti kata “tax relief” yang lebih positif dibanding “tax cut,” atau “death tax” yang menimbulkan penolakan publik lebih besar daripada “estate tax.” Dengan kata lain, bahasa adalah alat politik, ekonomi, dan budaya sekaligus.
Buku Words That Work pada akhirnya mengingatkan kita bahwa komunikasi yang efektif membutuhkan empati.
Seorang komunikator hebat bukanlah orang yang pandai berbicara, tetapi orang yang pandai mendengar apa yang orang lain pikirkan, rasakan, dan harapkan, lalu membingkai pesan dalam kata-kata yang beresonansi.
Inilah seni kata yang bekerja: sederhana, tepat, dan menyentuh hati. (*)