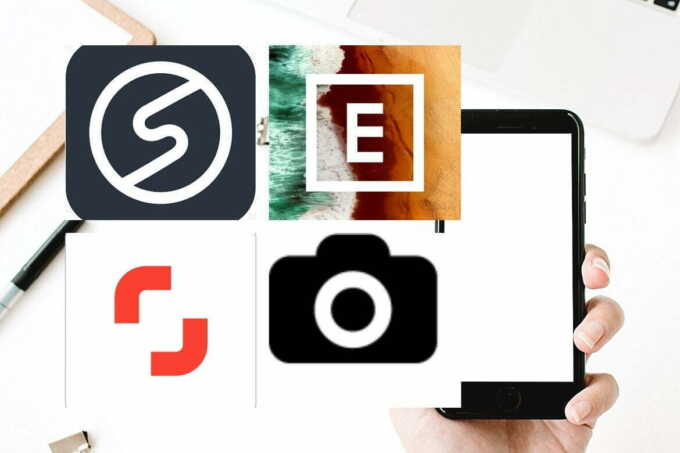Oleh: Dite Surendra News Editor Metrotoday (*)

BELAKANGAN, jagat maya ramai memperdebatkan keberadaan aplikasi jual-beli foto hasil jepretan fotografer jalanan di berbagai event, terutama lomba lari. Di aplikasi seperti Foto*u, kini fotografer pengguna aplikasinya dituding melanggar privasi dan bahkan disorot oleh Kementrian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Namun, di balik keramaian itu, banyak yang sesungguhnya belum memahami cara kerja dan manfaat sistem tersebut bagi fotografer konvensional maupun peserta acara lari atau acara lainnya.
Bagi fotografer lapangan, aplikasi seperti ini justru membuka lapangan kerja baru. Mereka memotret ratusan hingga ribuan peserta event, lalu mengunggah hasilnya ke sistem yang berbasis face detection.
Pengguna aplikasi wajib melakukan perekaman wajah saat mendaftar baik sebagai fotografer ataupun pelari atau bisa dua duanya. Dengan begitu, foto yang muncul di akun mereka hanyalah gambar wajah sendiri atau yang mirip –tidak bisa melihat atau membeli foto orang lain. Foto yang belum dibeli pun diberi watermark oleh sistem.
Artinya, tidak ada praktik “asal jepret lalu dijual sembarangan” sebagaimana dilakukan fotografer konvensional di tempat wisata. Semua pihak yang terlibat, baik fotografer (FG) maupun pengguna/pelari (runner), telah sama-sama menyetujui syarat dan ketentuan aplikasi. Bahkan jika ada kemiripan wajah, sistem memberi penalti bila seseorang membeli foto yang bukan miliknya.
Sayangnya, banyak pihak yang menolak tanpa memahami mekanisme aplikasi tersebut. Mereka menyamakan sistem digital ini dengan praktik “kang foto” untuk istilah fotografer konvensional, yang menawarkan hasil jepretan secara konvensional.
Padahal, pengguna aplikasi sudah secara sadar memberi izin melalui proses pendaftaran dan verifikasi wajah. Maka, wajar bila fotografer berharap hasil jepretannya bisa dihargai secara profesional melalui sistem yang aman dan tertib.
Lebih disayangkan lagi, muncul fenomena fotografer yang merasa memiliki “wilayah kekuasaan” di area publik. Hanya karena sudah lebih dulu motret di lokasi tertentu, mereka kerap mengintimidasi fotografer lain yang datang kemudian, seolah tempat tersebut adalah milik kelompok mereka.
Padahal, area publik semestinya tetap terbuka bagi siapa pun yang ingin berkarya dan mencari rezeki secara sehat. Tidak ada satu pihak pun yang berhak memonopoli tempat umum, apalagi dengan dalih “bayar izin” atau “terdaftar di manajemen tertentu, sementara tidak semua pengunjung memahami aturan semacam itu.
Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan soal privasi visual dan ruang publik belum dipahami secara menyeluruh. Ketika pemerintah atau penyelenggara event menggandeng aplikasi foto digital, artinya ada upaya menata sistem agar lebih profesional, transparan, dan adil bagi fotografer dan peserta acara.
Kalau dalihnya adalah pelanggaran privasi, mengapa instansi pemerintah maupun swasta justru memakai sistem yang sama untuk kegiatan resmi seperti fun run dan charity event?
Alih-alih membatasi, sebaiknya regulasi digital diarahkan untuk mendukung ekosistem kreatif dan memberi perlindungan bagi semua pihak.
Karena pada akhirnya, baik fotografer maupun pelari sama-sama ingin menikmati hasil karya dan momen yang mereka ciptakan tanpa prasangka, intimidasi dan saling menuding.
(*) Penulis merupakan pengguna aplikasi Foto*u, jurnalis foto lepas sekaligus fotografer komersil sejak 1999-hingga sekarang