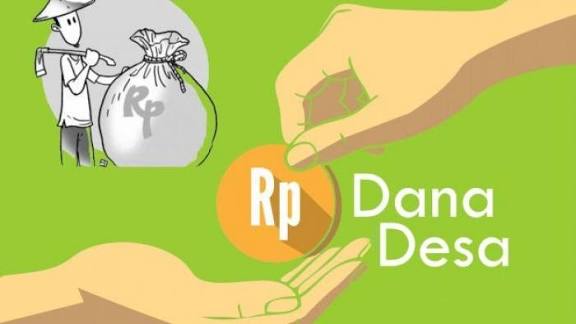Oleh: MUSONIF AFANDI, Direktur Eksekutif Actual Research Survey

SEJAK pertama kali digulirkan pada 2015, program Dana Desa telah menjadi salah satu kebijakan fiskal terbesar dalam sejarah pembangunan Indonesia. Total anggaran yang telah dialirkan ke desa-desa mencapai lebih dari Rp610 triliun dalam kurun satu dekade terakhir.
Tahun 2025 saja, pemerintah kembali mengalokasikan dana sebesar Rp71 triliun untuk memperkuat pembangunan di tingkat akar rumput. Besaran anggaran ini tidak hanya mencerminkan prioritas negara dalam membangun dari pinggiran, tetapi juga menunjukkan skala kepercayaan terhadap kapasitas desa sebagai motor pembangunan.
Di Jawa Timur, misalnya, hingga Juni 2024 realisasi Dana Desa telah mencapai Rp. 5,43 triliun dari total pagu Rp. 8,05 triliun. Angka-angka tersebut menegaskan bahwa desa kini menjadi arena strategis bagi pembangunan nasional sekaligus penggerak ekonomi lokal.
Namun, capaian fisik yang kasat mata belum selalu berbanding lurus dengan capaian ekonomi. Banyak desa kini memiliki jalan mulus, jembatan kokoh, dan balai desa yang megah.
Tetapi indikator kesejahteraan, pendapatan per kapita, serapan tenaga kerja, dan nilai tambah produk lokal, masih stagnan.
Sebagian besar Dana Desa masih terserap untuk proyek infrastruktur dasar, yang mudah dilaporkan dan difoto, tetapi sulit menunjukkan multiplier effect bagi ekonomi rumah tangga desa.
Dalam kerangka teori pembangunan daerah, infrastruktur dipahami sebagai syarat perlu, tetapi bukan syarat cukup, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Kehadiran jalan baru, jembatan, atau balai desa memang dapat membuka akses dan mobilitas, namun nilai tambah nyata hanya muncul bila infrastruktur tersebut dimanfaatkan oleh aktivitas ekonomi yang terorganisir.
Misalnya, rantai nilai pertanian yang efisien, usaha pengolahan hasil yang meningkatkan daya saing produk desa, hingga pengembangan pariwisata komunitas berbasis kearifan lokal.
Tanpa dukungan aktivitas produktif semacam itu, pembangunan fisik rentan berhenti sebagai output belanja semata, bukan outcome pembangunan yang menghadirkan pertumbuhan ekonomi, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat desa.
Dari Potensi ke Produktivitas
Pembangunan ekonomi desa tidak semestinya hanya dipahami sebagai urusan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tetapi sebagai upaya sistematis untuk menggerakkan seluruh potensi sosial, budaya, dan ekonomi yang ada di desa. BUMDes memang penting sebagai motor kelembagaan ekonomi, tetapi ia hanyalah salah satu instrumen dalam ekosistem pembangunan desa yang lebih luas.
Di banyak tempat, kekuatan desa justru berakar pada prakarsa warganya, seperti kelompok tani, komunitas perempuan, koperasi, pelaku UMKM, pemuda kreatif, hingga pengelola wisata lokal, yang bekerja bersama secara partisipatif.
Sayangnya, pendekatan pembangunan selama ini masih berorientasi proyek, fokus pada infrastruktur fisik, dan sering kali mengabaikan dimensi sosial-ekonomi yang bersifat jangka panjang.
Akibatnya, meski jalan desa membaik, aktivitas ekonomi produktif warga belum selalu tumbuh. Karena itu, transformasi paradigma pembangunan menjadi mutlak: dari infrastruktur ke produktivitas, dari program yang top down menuju kolaborasi yang berbasis potensi lokal dan aspirasi warga.
Pengalaman menunjukkan bahwa desa-desa yang tumbuh pesat adalah mereka yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai jantung pembangunan.
Desa wisata Nglanggeran di Gunungkidul, misalnya, membangun kemandirian ekonomi bukan hanya lewat BUMDes, tetapi melalui komunitas warga yang menjaga lingkungan, mengelola homestay, hingga memasarkan produk lokal.
Di Jawa Timur, kelompok perempuan di sejumlah desa memanfaatkan limbah pertanian menjadi kerajinan dan pupuk organik yang bernilai jual tinggi.
Gerakan seperti ini membuktikan bahwa kekuatan desa sesungguhnya ada pada inovasi sosial yang lahir dari partisipasi warga, bukan hanya pada besar kecilnya dana desa. Maka, peran pemerintah dan BUMDes seharusnya menjadi fasilitator, menciptakan ruang bagi ide, inisiatif, dan jaringan kolaborasi antar warga.
Pendampingan, akses permodalan mikro, serta literasi digital menjadi faktor krusial untuk memperluas dampak ekonomi lokal agar tak berhenti pada proyek sesaat, melainkan bertransformasi menjadi ekosistem ekonomi berkelanjutan.
Pembangunan ekonomi desa berbasis partisipasi dapat diperkaya dengan kerangka teori Community Development dan modal sosial (social capital).
Menurut pendekatan Community Development, proses pembangunan yang berkelanjutan menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan objek, perubahan, sehingga intervensi diarahkan untuk memperkuat kapasitas lokal dan mekanisme swakelola.
Sementara itu, teori social capital (Putnam) menekankan pentingnya kepercayaan, jaringan, dan norma gotong royong sebagai aset yang mempercepat koordinasi, menurunkan biaya transaksi, dan memungkinkan skala usaha kolektif.
Dalam konteks desa, kombinasi kemampuan teknis (capacities), modal sosial, dan akses jaringan pasar menentukan keberlanjutan transformasi dari proyek fisik menjadi usaha produktif.
Semakin tinggi kualitas partisipasi, termasuk keterlibatan perempuan dan pemuda, semakin besar kemungkinan inovasi lokal berkembang, risiko elite capture diminimalkan, dan hasil pembangunan dapat dinikmati secara inklusif.
Lebih jauh, pembangunan ekonomi desa yang kuat memerlukan sinergi antara komunitas lokal dan berbagai pihak eksternal seperti kampus, lembaga riset, sektor swasta, dan pemerintah daerah.
Desa harus dilihat sebagai laboratorium sosial ekonomi yang dinamis, tempat munculnya inovasi berbasis kearifan lokal. Dengan kolaborasi ini, potensi alam dan budaya desa dapat diolah menjadi sumber nilai tambah, mulai dari energi terbarukan, ekowisata, produk organik, hingga ekonomi digital.
Namun, semua itu hanya bisa berjalan jika warga memiliki peran nyata dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Partisipasi bukan sekadar hadir di forum musyawarah, melainkan menjadi kekuatan penggerak utama perubahan.
Generasi muda desa dengan kreativitas dan literasi digitalnya, dapat menjadi agen transformasi yang menjembatani potensi lokal dengan peluang global. Ketika energi kolektif ini disatukan, pembangunan desa tidak lagi bergantung pada dana, tetapi bertumpu pada daya, daya pikir, daya cipta, dan daya sosial masyarakatnya.
Dari sinilah produktivitas sejati desa akan lahir, ekonomi yang mandiri, berakar pada budaya, inklusif dan berorientasi masa depan.
Menuju Pembangunan Produktif
Kini saatnya Dana Desa memasuki fase kedua, yakni dari paradigma infrastruktur ke paradigma inovasi. Infrastruktur tetap penting, tetapi harus dilihat sebagai pondasi, bukan tujuan akhir.
Pertama, alokasi Dana Desa perlu diarahkan lebih besar untuk program produktif. Porsi minimal 30 hingga 40 persen bisa disyaratkan untuk usaha ekonomi dengan penguatan BUMDes, pelatihan kewirausahaan, pengolahan hasil pertanian, hingga pemasaran digital.
Indikator keberhasilan bukan lagi panjang jalan, tetapi jumlah usaha baru, serapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan warga.
Kedua, kapasitas manajerial desa harus diperkuat. Dana besar tanpa kemampuan teknis hanya melahirkan proyek jangka pendek. Universitas, lembaga riset, dan NGO perlu menjadi mitra desa dalam perencanaan bisnis, pelatihan keuangan, hingga branding produk lokal.
Model kemitraan desa dengan universitas sudah terbukti mampu menghubungkan produk desa ke pasar modern dan digital.
Ketiga, tata kelola partisipatif harus dipastikan. Transparansi anggaran desa melalui dashboard daring dan keterlibatan warga dalam evaluasi program akan menekan ruang elite capture.
Partisipasi yang substansial memastikan bahwa usaha produktif benar-benar menjawab kebutuhan komunitas. Keempat, akses pembiayaan dan pasar perlu diperluas. BUMDes bisa didukung melalui skema matching fund dengan bank daerah atau koperasi.
Digitalisasi pemasaran membuka peluang desa menjangkau pasar nasional dan global, tetapi ini menuntut literasi digital, logistik, serta sertifikasi mutu produk. Kelima, insentif ekonomi politik harus diubah.
Desa yang berhasil meningkatkan pendapatan warganya melalui usaha produktif perlu diberi penghargaan fiskal, bukan sekadar desa dengan laporan fisik proyek terbanyak. Dengan begitu, kompetisi antar desa diarahkan pada outcome, bukan sekadar output.
Dana Desa adalah pencapaian besar kebijakan publik. Namun, pembangunan berbasis infrastuktur tidak cukup untuk menjawab tantangan desa hari ini.
Paradigma baru harus ditekankan, desa sebagai subjek pertumbuhan, bukan objek pembangunan. Dengan kerangka ekonomi politik, kita melihat bahwa pergeseran ini tidak hanya soal teknis anggaran, melainkan juga soal distribusi kekuasaan lokal, insentif birokrasi, dan tata kelola partisipatif.
Jika Dana Desa diarahkan pada inovasi, partisipasi, dan produktivitas, maka jalan yang sudah dibangun benar-benar akan mengantarkan warga desa menuju kesejahteraan. (*)