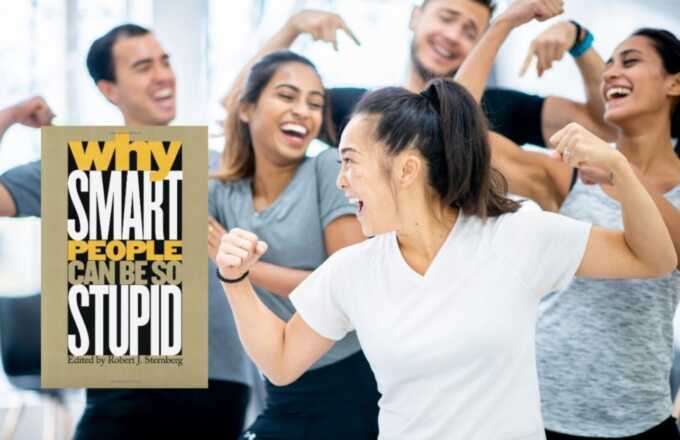Oleh: Edhy Aruman, Kolumnis dan Lecturer and Educator LSPR Jakarta
BILL Clinton adalah simbol paradoks kecerdasan. Dia lulusan Yale Law School dan peraih beasiswa Rhodes. Dia termasuk dalam segelintir individu dengan kecerdasan intelektual tertinggi.
Namun, dunia menyaksikan Clinton terjerembab dalam skandal seks yang nyaris mengguncang fondasi kepresidenannya.
Banyak yang menggelengkan kepala: bagaimana mungkin seorang pria secerdas Clinton bisa mengambil keputusan yang begitu sembrono?
Kisah ini bukanlah pengecualian langka. Ia justru menjadi potret umum bagaimana kecerdasan dan kebodohan bisa berdampingan dalam satu individu.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa kecerdasan bukanlah vaksin terhadap kebodohan. Clinton tidak kekurangan pengetahuan, logika, atau keterampilan komunikasi.
Ia hanya —seperti dijelaskan oleh Diane Halpern dan Robert J. Sternberg— gagal membaca ulang konteks sosial yang berubah, terjebak dalam pola pikir lama, dan terlalu mengandalkan keberhasilan masa lalu sebagai jaminan kelolosan dari konsekuensi yang baru.
Dalam istilah psikologis, ia mengalami disosiasi antara kecerdasan dan rasionalitas, yakni kegagalan menggunakan kapasitas intelektual secara optimal dalam pengambilan keputusan nyata.
Kasus Clinton mencerminkan apa yang disebut Keith E. Stanovich sebagai dysrationalia. Yakni ketidakmampuan untuk berpikir dan bertindak secara rasional meskipun memiliki tingkat kecerdasan tinggi.
Ini menjelaskan mengapa orang cerdas masih bisa mempercayai hal-hal keliru, membuat keputusan destruktif, atau mempertahankan keyakinan yang tidak logis.
Di sini, kecerdasan lebih mirip pisau: sangat tajam, tapi bisa melukai bila digunakan tanpa arah yang tepat.
Contoh lainnya datang dari Sol Wachtler, Hakim Agung New York yang terkenal akan keputusannya yang adil dan progresif. Namun kemudian –ini yang menarik– dia dipenjara karena meneror mantan kekasihnya.
Ia bukan kehilangan kemampuan berpikir, melainkan dikendalikan oleh emosi dan impuls, apa yang dalam teori dual-process disebut sebagai dominasi hot system atas cool system.
Logika dikalahkan oleh dorongan sesaat, dan hasilnya adalah kehancuran reputasi yang dibangun selama puluhan tahun.
Fenomena ini tidak terbatas pada individu dalam sistem hukum atau politik Amerika Serikat. Di Indonesia, kita juga menyaksikan bagaimana paradoks serupa terjadi, misalnya dalam gelombang flexing oleh sejumlah anggota DPR yang ramai dibicarakan publik.
Media sosial menjadi panggung untuk mempertontonkan tas mewah, jam tangan ratusan juta, hingga gaya hidup kelas jet set, yang dipamerkan tanpa rasa canggung di tengah krisis ekonomi dan ketimpangan sosial yang mencolok.
Publik bertanya-tanya: apakah mereka tidak menyadari ketimpangan ini? Atau lebih mengkhawatirkan lagi, apakah mereka justru tidak peduli?
Perilaku flexing semacam ini bukan hanya masalah etika, melainkan juga representasi dari mindlessness atau ketidaksadaran terhadap konteks.
Seperti dijelaskan Ellen Langer, mindlessness terjadi ketika individu merespons dunia dengan pola pikir lama yang tidak lagi relevan, sering kali karena dibentuk oleh lingkungan sosial yang sempit atau normatif.
Dalam dunia politik Indonesia yang masih kental dengan budaya patronase dan oligarki, gaya hidup mewah mungkin dianggap sebagai simbol keberhasilan, status, bahkan kewajaran.
Namun, dalam lanskap demokrasi yang menuntut transparansi dan empati sosial, perilaku tersebut berubah menjadi kebodohan yang memalukan.
Robert Sternberg menyebut fenomena ini sebagai hasil dari tiga ilusi. Yakni omnipotence (merasa sangat berkuasa), omniscience (merasa sangat mengetahui), dan invulnerability (merasa kebal).
Ketika seseorang sudah lama hidup dalam struktur kekuasaan, ia bisa kehilangan kepekaan terhadap realitas.
Kekuasaan memberi jarak, dan dalam jarak itulah kebodohan dapat tumbuh. Ia tidak datang dari ketidaktahuan, melainkan dari kepercayaan berlebih pada pengetahuan dan kekuasaan itu sendiri.
Orang cerdas sering terjebak dalam logika pembenaran diri. Leverrier, ilmuwan jenius penemu Neptunus, menghabiskan sisa hidupnya mencari planet fiktif bernama Vulcan, karena terjebak dalam kerangka teori gravitasi Newton yang ia yakini mutlak. Bukti yang bertentangan ia abaikan.
Ini disebut confirmation bias atau kecenderungan untuk menerima informasi yang mendukung keyakinan sendiri dan menolak yang bertentangan.
Orang biasa bisa salah. Tapi orang cerdas, ketika salah, sering menggunakan kecerdasannya untuk membela kesalahan itu dengan lebih pintar.
Dalam konteks kepribadian, Elizabeth Austin dan Ian Deary menunjukkan bahwa faktor seperti neurotisisme, narsisme, atau histrionik bisa membuat orang cerdas bertindak bodoh.
Perilaku pamer, haus pujian, dan ketidakmampuan mengendalikan emosi adalah ciri khas gangguan kepribadian yang sering tidak terlihat dalam skor IQ, tapi berdampak besar dalam kehidupan sosial.
Ini menjelaskan mengapa banyak individu cerdas di posisi tinggi tetap gagal membangun hubungan sehat, mengambil keputusan bijak, atau menjaga reputasinya.
Lebih dari itu, Carol Dweck menjelaskan bahwa keyakinan seseorang terhadap kecerdasannya juga memengaruhi perilakunya.
Orang dengan fixed mindset, yang percaya bahwa kecerdasan adalah sesuatu yang tetap, cenderung menghindari tantangan dan mempertahankan citra diri, bahkan dengan cara yang merusak.
Mereka lebih takut terlihat bodoh daripada menjadi benar. Maka tak heran jika banyak orang pintar justru tidak pernah mau belajar dari kesalahan.
Dalam semua ini, benang merahnya jelas: kebodohan bukanlah lawan dari kecerdasan, melainkan kegagalan dalam mengaplikasikan kecerdasan secara adaptif.
Bukan karena tidak tahu, tetapi karena tidak sadar. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena terlalu yakin.
Kecerdasan tanpa kebijaksanaan hanya akan menjadi pedang tanpa arah, tajam tapi membahayakan pemiliknya.
Di dunia yang kompleks seperti hari ini, kita tidak hanya butuh orang-orang cerdas. Kita butuh orang yang bijak, yang mampu menahan diri dari dorongan sesaat, yang bisa melihat diri sendiri dari kacamata orang lain, dan yang berani berkata: “Saya mungkin pintar, tapi saya juga bisa salah.”
Dan itu, mungkin, adalah puncak kecerdasan yang sesungguhnya. (*)